Meranti merupakan salah satu jenis flora yang sudah tidak perlu diragukan lagi kepopulerannya di Indonesia, baik dari segi peran besar yang dimiliki terhadap lingkungan maupun keberadaannya yang berharga jika dilihat dari segi ekonomi sebagai hasil dari tanaman hutan produksi. Pohon meranti selama ini dikenal memiliki banyak manfaat karena buah dan …
Read More »Kenapa selada jadi tanaman yang banyak dipilih dalam hidroponik?
Rasanya mustahil ada yang tidak mengenal selada. Jenis sayur satu ini banyak ditemukan di berbagai jenis makanan seperti salad hingga lalapan. Banyak disukai, selada nyatanya juga menjadi jenis sayur yang banyak dipilih dalam praktik hidroponik. Fakta menarik lainnya, selada bisa dibilang menjadi salah satu jenis sayur yang paling banyak dan …
Read More »Mengenal Narwhal, paus bertanduk sang ‘unicorn laut’
Jika mendengar kata unicorn, gambaran yang akan terlintas di pikiran adalah makhluk mitologi berupa kuda dengan tanduk di bagian ujung kepalanya. Saat ini keberadaan unicorn sendiri memang masih menjadi misteri. Tapi di luar cerita mitologi, rupanya ada makhluk yang kerap disebut sebagai unicorn di dunia nyata, yakni Narwhal. Bukan di …
Read More »Anoa, spesies kunci endemik dari Sulawesi
Masuk dalam ordo dan spesies sama dengan kerbau yakni Bubalus sp., belum banyak yang tahu jika anoa adalah jenis kerbau terkecil di dunia. Karena ukurannya yang terbilang kecil, anoa kerap disebut sebagai kerbau kerdil atau kerbau cebol. Dalam spesies Bubalus, diketahui jika hanya tersisa lima spesies keluarga kerbau yang masih …
Read More »Mengenal buah salju, benarkah punya sensasi dingin alami saat dimakan?
Buah-buahan begitu disukai karena banyak memiliki kandungan air. Bahkan dalam kondisi tertentu, ada yang mengonsumsi buah dengan cara olahan dingin seperti dijadikan es, salad, dan lain-lain. Tapi apa jadinya kalau ternyata ada buah yang aslinya sudah memiliki sensasi dingin? Yaitu buah salju. Iya, tanpa perlu dimasukkan dalam kulkas, diolah menjadi …
Read More »Sawen dan ikhtiar keselamatan hidup manusia
Nusantara mempunyai keragaman budaya yang sangat banyak dan salah satunya pada suku Sunda yang kini menempati provinsi Banten, Jawa Barat, sebagian DKI Jakarta dan juga sebagian wilayah barat Jawa Tengah. Persoalan yang menyangkut nilai dalam kebudayaan, pada umumnya terdapat lima hal, yaitu; makna hidup manusia, makna pekerjaan, persepsi mengenai waktu, …
Read More »Hiu megamouth, spesies langka yang hidup di perairan Indonesia
Hiu bermulut besar (Megachasma pelagios) adalah spesies hiu yang sangat langka. Hiu ini ditemukan pada tahun 1976. Hanya sedikit hiu ini yang telah terlihat dengan 39 spesimen telah ditangkap atau dilihat. Hiu ini berenang dengan mulut terbuka untuk makan plankton dan ubur-ubur. Hiu yang dinamakan megamouth tersebut juga hidup dalam …
Read More »7 hewan kanibal yang mampu memangsa sesama spesiesnya
Klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan yang dapat dikonsumi lazimnya dibedakan menjadi 3. Yakni Karnivora pemakan daging, herbivora pemakan tumbuh-tumbuhan, dan omnivora pemakan segala. Adapun pemakan segala bagi omnivore juga mencakup biji-bijian dan sejenisnya. Sementara itu bagi hewan karnivora umumnya memburu hewan yang lebih lemah dan memang menjadi mangsanya dalam rantai …
Read More »Ini dia, 7 burung endemik yang mendiami wilayah Ranca Upas
Belakangan, media sosial dan pemberitaan daring diramaikan dengan aktivitas komunitas motor trail di wilayah konservasi satwa Ranca Upas, Bandung, yang berujung rusakya habitat lingkungan di sana. Ranca Upas adalah sebuah daerah wisata yang terletak di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia, yang berada di ketinggian sekitar 1.600 mdpl. Kawasan itu juga …
Read More »Luas laut dan perairan di Indonesia
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas perairan dan laut yang cukup besar. Luas perairan di Indonesia diperkirakan sekitar 3,2 juta km persegi, yang terdiri dari laut teritorial seluas 2,8 juta km persegi dan laut ekonomi eksklusif seluas 300 ribu km persegi. Luas laut di Indonesia ini merupakan salah satu …
Read More »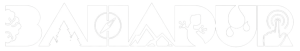 Bahadur.id Bahadur Indonesia adalah Blog berbasis komunitas yang mengangkat isu sosial, lingkungan, kultur/budaya, teknologi, dan data sains
Bahadur.id Bahadur Indonesia adalah Blog berbasis komunitas yang mengangkat isu sosial, lingkungan, kultur/budaya, teknologi, dan data sains







